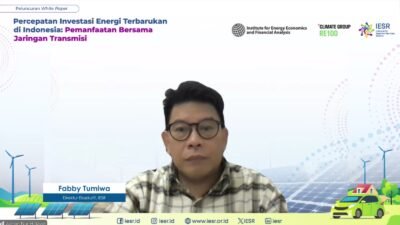JAKARTA, literasikaltim.com — Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kemandirian energi, melalui pemanfaatan energi terbarukan mendapat dukungan serius dari Institute for Essential Services Reform (IESR).
Menyikapi proyeksi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diproyeksikan mencapai 108,7 GW pada tahun 2060 sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), IESR bersama Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis rekomendasi Peta Jalan Rantai Pasok Industri Fotovoltaik Terintegrasi di Indonesia.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya telah menyatakan bahwa pengembangan energi surya merupakan langkah strategis menuju kemandirian energi nasional, terutama dimulai dari desa-desa.
Dalam Forum Internasional KTT BRICS, Presiden juga menegaskan optimismenya bahwa Indonesia mampu beralih 100% ke energi terbarukan, dalam waktu 10 tahun, dengan energi surya sebagai tulang punggungnya.
Meski dinilai masih jauh dari implementasi nyata, IESR menilai ambisi tersebut perlu didorong melalui perencanaan konkret di luar mekanisme formal seperti RUPTL, dengan menekankan pentingnya membangun ekosistem industri energi surya dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.
“Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat produksi teknologi fotovoltaik di Asia Tenggara,” ucap Fabby Tumiwa, CEO IESR.
“Tapi kita harus mulai dari sekarang, membangun ekosistem industrinya dari bahan baku, teknologi, sampai kerangka kebijakan,” ujarnya.
Fabby menjelaskan, tingginya permintaan global terhadap PLTS, ditambah dengan dorongan Net Zero Emission (NZE) di berbagai negara, membuka ruang besar bagi Indonesia, untuk masuk sebagai alternatif rantai pasok internasional, yang selama ini didominasi Tiongkok.
Lokasi strategis Indonesia, dan melimpahnya sumber daya mineral kritis, seperti pasir kuarsa menjadi keunggulan tersendiri.
“Lebih dari 17 miliar ton pasir kuarsa tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, dan Kita punya modal besar untuk memproduksi polisilikon secara lokal, yang bisa menekan biaya hingga di bawah USD 9 per kilogram,” tambahnya.
Menurut analisis IESR, kapasitas produksi dalam negeri untuk modul surya telah mencapai 10,6 GW dan sel surya 9,5 GW, namun utilisasi masih rendah karena minimnya permintaan domestik.
Sementara itu, komponen industri hulu seperti polisilikon, ingot, wafer, dan kaca tempered rendah besi masih harus diimpor.
Alvin Putra Sisdwinugraha, analis sistem ketenagalistrikan dan energi terbarukan IESR, menambahkan bahwa peluang Indonesia sangat besar, untuk menjadi pemain industri surya global, apalagi tren ekspor teknologi dan minat investasi juga terus meningkat.
“Produksi modul lebih mudah dimulai, terutama dengan dukungan industri penunjang seperti aluminium dan kaca, dan Kita hanya butuh dukungan kebijakan agar industri ini bisa naik kelas ke skala global,” katanya.
Kajian IESR merekomendasikan pembangunan rantai pasok fotovoltaik melalui tiga fase waktu:
- Jangka pendek (2025–2030): peningkatan permintaan dan investasi awal
- Jangka menengah (2031–2040): integrasi teknologi dan penguatan industri lokal
- Jangka panjang (2041–2060): ekspansi global dan dominasi rantai pasok Asia-Pasifik
Langkah strategis ini disarankan diiringi dengan pembentukan kelompok kerja lintas sektor, insentif fiskal dan nonfiskal, harmonisasi tarif dan bea masuk, serta kebijakan harga preferensi untuk modul lokal.
Pada tataran regional, Indonesia didorong menjalin kerja sama di bawah kerangka AFTA, membangun pusat R\&D terintegrasi, mempercepat otomasi pabrik, dan memastikan transfer teknologi melalui kerja sama investasi.
“Semua inisiatif ini dapat diintegrasikan dalam bentuk konsorsium nasional, untuk menghubungkan sektor hulu dan hilir industri energi surya, dalam satu ekosistem yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan,” ujar Fabby.
IESR menyebut, transformasi ini mendesak dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga produsen global yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam ekonomi hijau dunia.
REDAKSI